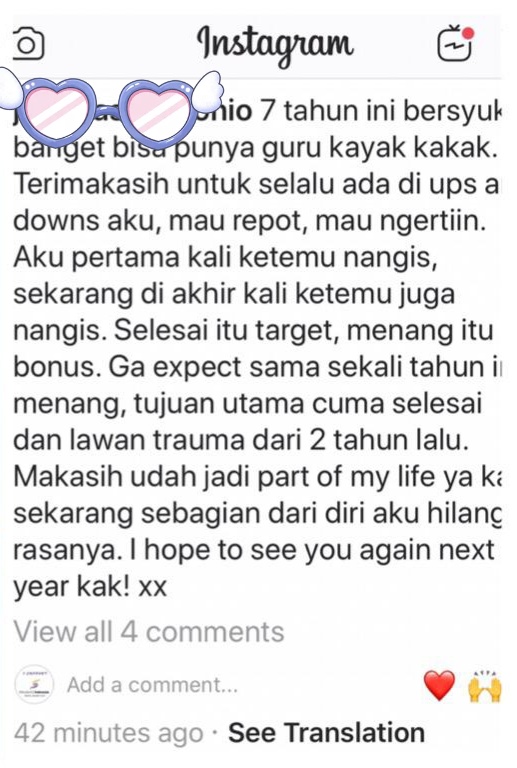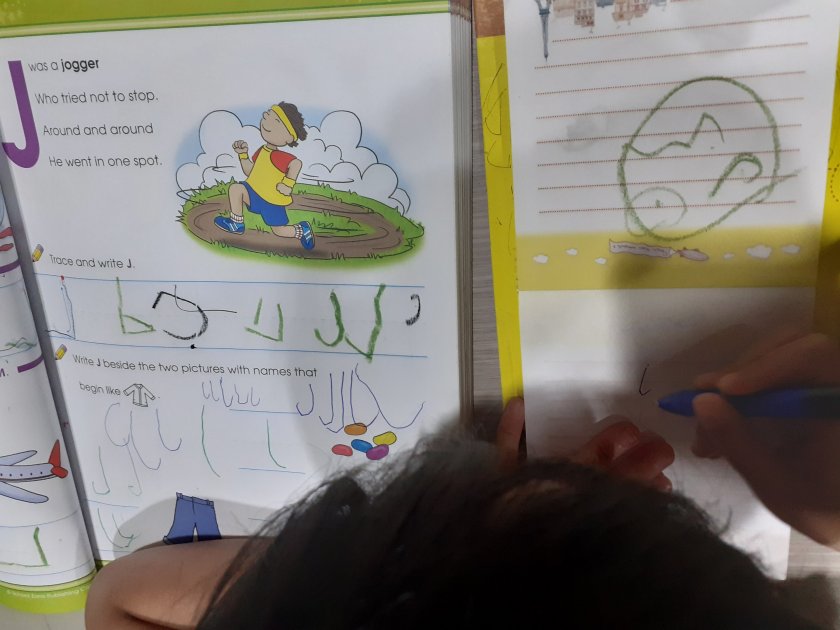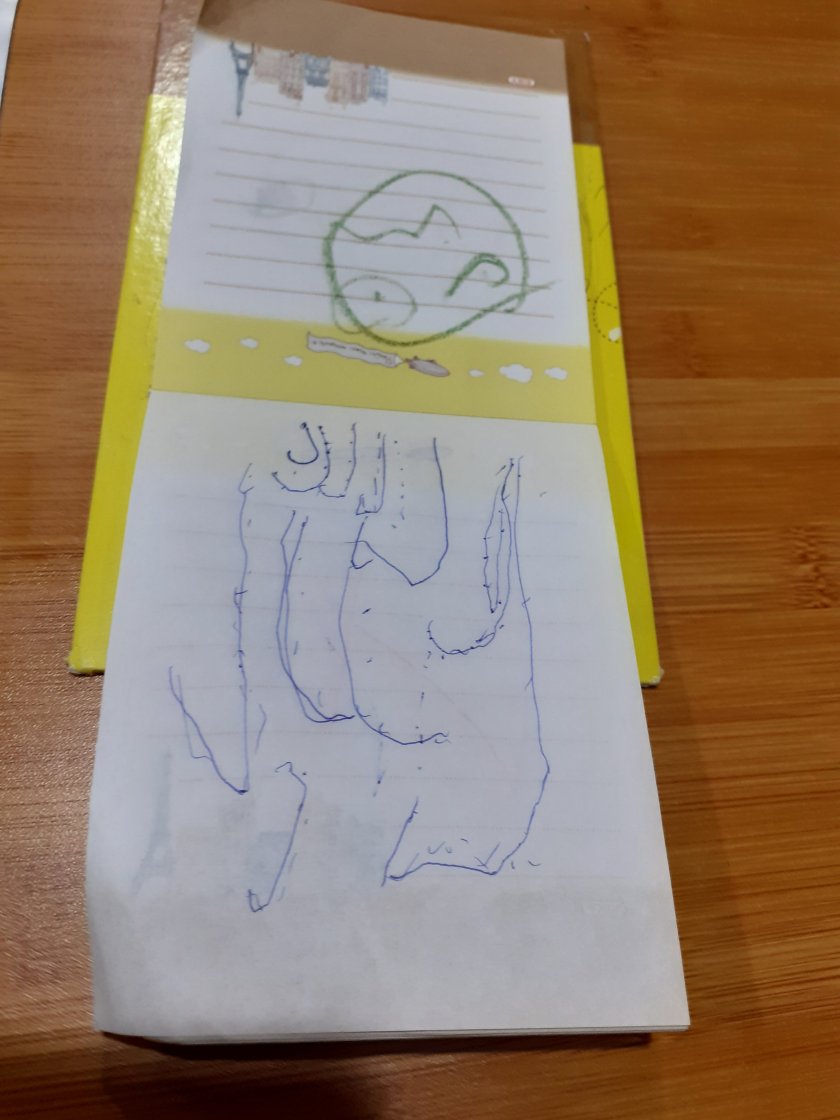Masih dalam suasana eforia hari Minggu kemarin.
Mau cerita tentang Jessica. Salah satu murid yang diajar dari dia kelas 4 SD dan sampe sekarang dia kelas 1 SMA. Salah satu murid pertama sejak ngajar di sana. Rajin, selalu sopan, sederhana, dan punya determinasi yang tinggi. Tipe murid top student yang nilainya bagus, ketua osis, sibuk, tapi hampir ngga pernah saya inget dia ngga les piano karena ada ulangan atau kegiatan apapun.
Punya kakak tapi seperti anak tunggal karena kakak laki-lakinya di luar negeri. Papa mamanya sibuk, dan sehari-hari diurus mbaknya. Belakangan mamanya udah pensiun jadi sering anter les.
Sejak kompetisi pertama kali ada, dia udah saya ikutin. Pertama masuk di Junior B. Tiga tahun berturut-turut ikut kompetisi, tiga-tiganya pegang piala. Pertama kali juara dua, lalu harapan satu, dan tahun terkahir di kategori B juara tiga.
Tahun berikutnya pindah ke kategori C karena umur. Persaingan dan tekanannya naik jauh sekali dari B ke C. Menang di kompetisi itu kombinasi dari banyak hal. Tapi, menurut saya selalu diawali dari satu hal penting, yaitu pemilihan lagu.
Lagu yang dipilih harus ngga pasaran, jarang dimainkan tapi enak didengar, tingkat kesulitan kalau bisa sedikit di atas standar kategori yang diikuti, dan terakhir, anak yang mainin suka lagunya.
Selama tiga tahun di kategori B, alhamdulillah saya selalu pilih lagu yang pas buat dia. Milihnya pun lama karena selalu saya coba sendiri dulu dan saya bayangin kesulitan yang bakal ada pas belajar, sambil memperhitungkan kemungkinan ada orang lain yang milih lagu ini. Selama tiga tahun di kategori B, semua faktor resiko sudah dieliminasi. Ditambah penentuan akhir dimana dia bawain lagunya dengan pede dan bagus, tiga tahun berturut-turut namanya selalu disebut ketika pengumuman juara.
Tahun ke empat kompetisi saya tawarin lagi buat ikut. Lagu udah saya pilih dan siapin sejak lama. Tapi memang dari awal seperti ada yang kurang atau kaya ada yang salah aja di kompetisi tahun 2017 itu. Mungkin karena setelah tiga kali ikut dan menang, baik guru dan muridnya pun ekspektasinya juga cukup tinggi. Jadi, agak berat juga beban dari awal.
Lagu yang dipilih October Tchaikovsky. Salah satu lagu favorit saya. Lagu yang cukup bagus buat kompetisi pertama dia di kategori C yang persaingannya lebih sulit. Lagunya bagus, dia juga suka, dan ngga terlalu panjang. Lambat dan pelan. Pressure sedang, kans buat menang juga cukup besar, kalo dimainkan dengan baik.
Sampai sekitar sebulan atau dua bulan sebelum kompetisi, kita tau ada satu anak lain main lagu yang sama. Murid guru lain yang juga sering jadi juara kompetisi. Saya dan dia langsung agak pucet waktu tau tentang itu. Main lagu yang sama ngga pernah menguntungkan buat pesertanya.
Ganti lagu sempet jadi pilihan tapi liat waktu latihan dan chemistry yang harus dibangun lagi dengan lagu barunya, kita mutusin buat tetap jalan. Sambil berharap semoga saat pengambilan undian dia dapet main yang duluan.
Di hari pengambilan undian, perasaan salah yang dari awal ada makin besar. Jessica dapet yang belakangan cuma dengan jeda 1 anak. Bebannya makin besar sekali di dia.
Di hari Gladi resik, dia main bagus sekali. Saya jadi agak tenang. Apalagi setelah denger saingan yang mainin lagu yang sama. Dalem hati paling ngga punya harapan lebih.
Hari H, ketemu dia dengan baju kompetisinya yang manis, Jessica keliatan cukup nervous. Wajar sih. Seperti biasa saya nemenin dia sambil ingetin beberapa instruksi yang dia kadang-kadang salah. Waktu giliran peserta lagu yang sama maju dan main, mungkin saat itu mentalnya semakin jatuh. Anak itu main dengan bagus, manis, dan bersih sekali. Bener-bener bersih dan tepat sekali semua dinamiknya. Perasaan saya semakin ngga enak tapi tetap berusaha semangatin dia.
Ketika gilirannya maju, dia terlihat ngga nyaman sekali. Not pertama dimainkan dengan sangat ragu-ragu. Not pertama dan bar pertama itu kunci yang nentuin mood dan tempo lagu seterusnya. Seringnya, ketika itu ngga dapet, kemungkinan memperbaikinya agak sulit.
Dan, selang beberapa menit kemudian, kejadian yang paling menakutkan terjadi. Sampai hari ini masih satu-satunya di sepanjang kompetisi yang pernah ada di sekolah musik ini.
Jessica berhenti main dan keluar panggung sambil nangis dan bilang, “aku ngga bisa, aku ngga bisa,”.
Ngga bisa digambarin perasaan saya waktu itu. Sedih, kecewa, patah hati, tapi saya juga sangat ngerti besarnya beban mental yang dia harus hadepin di depan.
Ternyata patah hatinya belum selesai. Saat pengumuman pemenang, juara pertama jatuh ke anak lain dengan lagu yang sama dengan Jessica. Disini, setidaknya kita tau, saya tidak salah pilih lagu.
(Pernah dibahas lengkap di post ini)
Kita ngga banyak bahas itu setelahnya. Les pun kembali berjalan seperti biasa.
Kompetisi tahun 2018 dia menolak ikut karena alesannya sedang sibuk di sekolah. Tapi, tentu bukan cuma karena itu. Kita sama-sama tau kalo trauma dia masih besar. Saya pun ngga mau maksa.
Tahun 2018 saya bisa fokus ke satu murid baru yang cukup bagus dan saya ikutkan juga kompetisi karena liat potensinya. Alhamdulillah, seperti yang diharapkan, Nathan juara 1 di kompetisi pertamanya.
Awal tahun 2019, sudah diumunkan kompetisi akan diadakan bulan Agustus. Di awal tahun ini juga, wacana saya kemungkinan besar akan harus resign mulai mencuat. Di bulan Maret, saya mulai nanya ke dia apa mau coba ikut lagi. Saya bilang saya udah siapin lagunya. Dia bilang mau mikir dulu. Saya tegaskan ke dia kalo saya ngga mau maksa. Tapi, saya mau dia basuh dulu traumanya dua taun lalu dengan ikut lagi, main sampai selesai, ngga peduli apapun. Cukup itu. Ngga perlu mikirin menang dan yang lain. Cukup main dari awal sampai akhir, ngga peduli sejelek apa.
Bulan April dia ujian nasional dan akhirnya dia setuju ikut setelah dia selesai ujian. Saya sudah pilih dua lagu yang kontras. Satu lagu pendek 3 halaman, lambat, dan cukup terkenal, cocok sekali kalo targetnya cuma buat sekedar hilangin trauma. Satu lagu lainnya cepat, panjang 6 halaman dengan not yang banyak, dan jarang orang akan pilih dan mainkan. Bahkan mungkin jarang tau juga.
Saya bilang ke dia kalo saya sengaja kasih yang sangat kontras seperti ini. Biarpun jelas sekali yang mana preferensi saya, saya biarin dia tetap milih. Bukan sekedar milih lagu, tapi juga memilih sampai level mana yang mau dia capai. Dari situ saya bisa tentuin sikap harus seperti apa drilling dia.
Sesuai ekspektasi saya tentang dia selama ini, tentu dia pilih yang punya kesempatan lebih.
Dalam kompetisi, saya selalu punya target yang mau dicapai. Tentu sesuai kapasitas muridnya. Meskipun orang sering bilang, ikut aja yang penting pengalamannya. Latihan berani tampil dan sebagainya. Tapi, buat saya ngga. Kalo cuma itu ada konser.
Apa kalo kompetisi harus menang? Tidak. Karena menang atau kalah ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Tapi, yang harus ditargetkan adalah, di kompetisi ada menang dan kalah, apa kita mau kalah atau menang? Tentu jawabannya jelas.
Dengan tau target, kita jadi tau harus seberapa keras usahanya untuk itu. Karena beda sekali orang yang tujuannya cuma sekedar ikut dan orang yang punya target jelas.
Saya bilang ke murid-murid saya, ikut kompetisi persiapan tidak boleh 100%. Minimal 150%. Grogi itu menurunkan kemampuan sampai 50 %, apa jadinya kalo cuma siap 100%.
Balik ke persiapan kompetisi. Selama latihan terus terang progresnya ngga terlalu bagus dan agak lambat. Saya sempet agak frustasi dan marah ke dia. Saya tanya mana komitmennya. Saya tau lagunya susah, tapi menurut saya ada saat di mana dia ngga berusaha maksimal buat latihan. Enam minggu sebelum kompetisi, masih 3 halaman yang dia belum beres. Belum hafal not, dinamik, banyak sekali bagian yang harus drilling dsb.
Di beberapa bagian bahkan ada yang saya sampai suruh dia ulang berkali-kali sampai dia bisa, baru boleh pulang. Di sebulan terakhir, saya paksa dia tutup partitur. Kalo bayangin waktu itu, betul-betul khawatir tinggal 4 minggu hafal sedikit pun belum. Enam halaman panjang.
Ngeliat ini, saya putuskan buat nambah jam lesnya di hari lain. Berlaku juga buat Nathan, yang ndilalahnya, kok mainnya juga malah jadi turun. Sempet gelisah sekali saya liat dua orang ini. Lebih gelisah lagi karena ngebayangin saya akan resign. Gelisah karena ngebayangin hari terakhir saya akan diinget seperti kegagalan.
Ngga ada gunanya pernah juara tiga kali dan juara satu tahun lalu, orang hanya akan ingat yang terakhir kali ditorehkan. Dengan Jessica, bahkan yang diingat pengamalan buruk tahun 2017. Agak patah hati saya ngebayangin kalo 15 tahun saya ngajar seperti ngga keliatan hasilnya.
Kasih jam tambahan itu sulit sekali dari sisi saya. Karena waktu terbatas. Akhirnya saya paksakan untuk kasih mereka waktu tambahan di hari di mana saya punya waktu 1 jam sembari Langit les. Jadi saya drop Langit, lalu lari ngajar 2 orang dan kembali ke jemput Langit, semua dalam waktu 1 jam.
Pernah saya tergoda sekali buat batalin. Apalagi hari tambahannya di hari saya puasa juga. Tapi, alhamdulillahnya otak dan hati cukup keras, sambil marahin diri sendiri, ” Kalo nanti hasilnya ngga bagus, lo akan nyalahin diri sendiri kenapa ngga usaha lebih padahal bisa, cuma karena capek dan lemes. Akan lebih lemes kalo nyesel belakangan,”.
Dua minggu terakhir tensi dan suara saya makin tinggi. Ngga terhitung seringnya saya scolding mereka berdua sampe pucet.
Di hari kamis sebelum kompetisi, Nathan udah ada titik terang. Tapi tidak dengan Jessica. Salah masih banyak, hafalan lumayan tapi masih suka bener-bener blank di tengah jalan, dan yang paling mengkhawatirkan nervousnya juga tinggi sekali. Tiap main pasti tiba-tiba berhenti dan panik sendiri.
Saya terus ingetin dia supaya tenang dan fokus. Ingetin dia kalo hal utama yang harus dia capai hanya main sampai selesai. Itu udah lebih dari cukup. Saya tau enam halaman itu panjang dan dia harus mainkan dengan tempo yang beda, dan notnya cukup sulit, dimana kalo dia salah bisa merembet kemana-mana, meskipun dia juga udah tau teorinya kalo salah yang harus dilakukan adalah jalan terus.
Hari Sabtu gladi resik, saya makin khawatir karena nervousnya dia terasa makin tinggi. Percobaan pertama maju di panggung, gagal total. Bahkan sampe nangis lagi. Saya dan mamanya terus nyemangatin. Di percobaan ke sekian kali saya liat ngga ada perubahan sama sekali. Semua latihannya ketutup sama tingginya nervous dia. Gladi resik awalnya cuma 10 menit. Saya minta ijin lagi ke ibunya buat latihan lagi di ruangan sampai molor jadi 1,5 jam.
Di ruangan saya suruh dia drilling halaman pertama sampe puluhan kali. Bolak balik hanya halaman pertama. Kuncinya hanya itu. Begitu halaman pertama dia aman, pede dia langsung naik drastis. Setelah dirasa cukup halaman pertama, saya suruh dia drilling 4 baris terakhir berkali-kali.
Seperti semua hal dalam hidup, ngga peduli bagaimana kita mulai, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita selesai. Begitu juga dengan lagu.
Setelah kurang lebih setengah jam atau empat puluh menit latihan di kelas, emosinya udah lebih tenang, saya ajak dia latihan di showroom bawah pake piano grand di ruangan terbuka. Cukup berhasil. Dia udah lebih tenang, meskipun beberapa spot masih salah-salah. Secara keseluruhan aman, tapi tidak memuaskan.
Setelah dari bawah, saya ajak balik ke ruangan gladi resik. Saya minta dia main bagian yang tengah aja. Bagian yang perlu pedal dan paling aman. Saya larang buat main dari awal sampe akhir. Setelah main dari tengah saya minta dia main halaman pertama dan empat baris terakhir. Setelah itu saya cukupkan dan minta dia pulang buat istirahat.
Ngga nyangka yang awalnya niat saya cuma dateng 15 menit, berakhir jadi 2 jam. Tapi, kalo inget sekarang, saya senang karena udah milih yang benar dibanding yang mudah.
Nathan gimana? Alhamdulillah aman. Setidaknya kalo dia main seperti hari kamis dan sabtu gladi resik, setidaknya satu tempat juara udah dia amankan. (Kok pede? Iya, anaknya juga pede banget gitu mainnya).
Hari Minggu saya bangun dengan perasaaan sedikit khawatir dan banyak pasrahnya. Hari itu akan jadi penentuan bukan cuma buat murid-murid saya, tapi lebih ke diri sendiri. Akhir seperti apa yang (pantas) saya dapatkan?
Semua usaha sudah dilakukan (semaksimal dan semampu saya). Seluruh doa juga ngga berhenti dipanjatkan.
Saya dateng setelah zuhur. Waktu dateng kompetisi sudah dimulai. Biasanya saya masuk ke ruang penonton atau ruang tunggu bareng guru lain. Tapi ini, saya milih buat tunggu di luar yang sepi. Jantung kaya mau copot.
Nathan di kategori B maju duluan. Waktu saya ketemu dia, dia keliatah cukup tenang dan percaya diri yang cukup. Saya pernah ingetin dia, tidak boleh over confident karena itu yang kadang bisa buat hilang fokus. Seperti di beberapa latihannya yang salah di not terakhir.
Saya udah janji buat kali ini saya ngga akan masuk. Saya hanya akan dengar dari luar pintu. Begitu Nathan naik, yang saya bisa kerjain cuma baca Al-ikhlas setengah keras buat nutupin suara mainnya dia yang tetep lebih keras. Ngga berhenti saya doa.
Nathan main dengan bagus sekali. Bersih, powerful, dan rapi.
Seperempat beban diangkat alhamdulillah.
Jarak Nathan ke Jessica cukup jauh. Saya tetap ngga mau masuk ke dalem kursi penonton dan ruang tunggu. Waktu saya masih duduk, Jessica dan mamanya keluar. Mamanya bilang minta keluar dulu.
Saya agak tercekat liat baju yang dia pakai. Seinget saya yang paling minim standarnya dari selama ini dia ikut kompetisi. Kombinasi kaos dress softball selutut yang kalo dia duduk jadi ketarik dan agak pendek, juga sepatu wakai dengan warna senada.
Tapi ya sudah. Ngga ada gunanya meributkan masalah baju ketika ada isu yang lebih besar.
Ketika dia sudah dipanggil ke ruang tunggu, saya masih milih nunggu duduk di luar. Saya rasa waktu itu, saya dan dia punya battle masing-masing yang harus dihadapi sendiri. Dia yang harus melawan trauma dan ketakutannya. Saya yang harus mempersiapkan diri buat nerima kemungkinan terburuk di akhir perjalanan mengajar saya.
Saya masuk ke ruang tunggu ketika giliran dia tinggal 3 lagi. Waktu giliran dia tiba, seperti yang saya lakukan dengan Nathan, dia masuk ke atas panggung, saya keluar dan turun ke bawah tangga di samping. Saya terlalu nervous untuk berdiri di depan pintu seperti yang saya lakukan dengan Nathan.
Detik dia masuk, mulut saya ngga berhenti merapalkan Al-ikhlas. Saya terus baca sampai kadang saya pikir saya berdoa supaya ngga terlalu denger jelas permainan dia. Betul-betul ngga baik buat jantung.
Tentu permainannya tetap terdengar jelas. Dan sedikit tapi pasti, hati saya mulai ringan. Dia berhasil melewati halaman pertamanya dengan baik. Halaman kedua percaya diri naik. Halaman ketiga seperti yang sudah diprediksi adalah yang paling aman. Harapan saya semakin naik ketika di halaman keempat di bagian yang dia selalu miss, dimainkan dengan rapi dan bersih. Zikir saya mulai diganti senyum sambil sedikit nangis.
Halaman kelima dan ke enam, Jesssica seperti balik ke Jessica versi terbaiknya. Bagus sekali penutup yang dia mainkan.
Turun dari panggung dan keluar ruangan, kita berdua berpelukan dan dia bilang, ” aku bisa kak,”.
Ternyata selesai dia main, mama papanya pun juga langsung keluar dengan wajah sumringah sambil ngacungin jempol.
Setelah itu, saya kaya ikan yang dikembalikan ke air.
Tiga perempat dari beban saya sudah diangkat bersih.
Tinggal seperempat terakhir.
Pengumuman pemenang dimulai dari kategori B. Terus terang saya ngga terlalu khawatir. Dengan adanya 6 piala buat kategori B, Nathan hampir pasti dapat salah satunya.
Ketika sampai di pengumuman juara ketiga dan nama dia belum ada, saya agak sedikit khawatir kalo saya bisa aja salah total. Juara kedua diumumkan juga bukan dia.
Nama Nathan akhirnya disebut paling terakhir.
Seperdelapan beban saya diangkat bersih kembali. Setidaknya untuk Nathan dan orangtuanya, saya akan diingat sebagai guru yang selama 2 tahun ngajar dia, ada memori sesignifikan 2 kali kompetisi 2 kali pegang piala juara pertama.
Tiba giliran pengumuman kategori C.
Waktu itu saya ngga inget harus ngharep apa. Mau ngharep menang kok kaya ngerasa ngelunjak, tapi ngharep ga menang juga gimana, mainnya bagus dan lebih dari cukup dibanding lawan-lawannya untuk pegang satu piala.
Ada 4 juara di kategori C. Nama yang disebut pertama bukan Jessica. Masih lega saya. Saya banyak berharap di ketiga dan kedua. Ternyata di ketiga pun bukan dia. Saya mulai sedikit nelen ludah. Harapan saya tinggal sekali lagi.
Nama yang berikutnya disebut juga bukan Jessica dan saat itu saya sudah telen seperdelapan beban terakhir yang ngga bisa hilang di hari terakhir saya.
Saya ngga akan lupa momen dimana ketika MC ngumumin juara pertama.
Sampai ngga bisa kontrol suara dan air mata.
Nathan juara pertama mungkin ngga luar biasa, tapi Jessica bisa juara pertama, di hari terakhir saya, setelah semua senang sedih yang kita lewatin sama-sama selama 7 tahun, setelah kejadian luar biasa dua tahun lalu, saya terlalu bersyukur sekali dianggap pantas nerima hasil akhir sebaik ini. Dan saya benar-benar salut dan bangga sama anak ini. Bisa ngalahin ketakutannya, bisa ngalahin traumanya, dia pantes jadi juara satu. Dia naik ke panggung sambil nangis.
Tidak ada yang lebih menyenangkan dari perasaan lega bisa kasih selamat ke orang tua Jessica dengan level yang sama seperti saya memberi selamat ke orang tua Nathan.
Dengan berakhirnya kompetisi di Minggu, 25 Agustus 2019, berakhir juga perjalanan saya selama 15 tahun di sekolah ini.
Ngga berhenti saya bersyukur buat semua yang dikasih hari itu, jauh di luar dari yang saya berani bayangkan.
Alhamdulillah alhamdulillah untuk epilog ini.
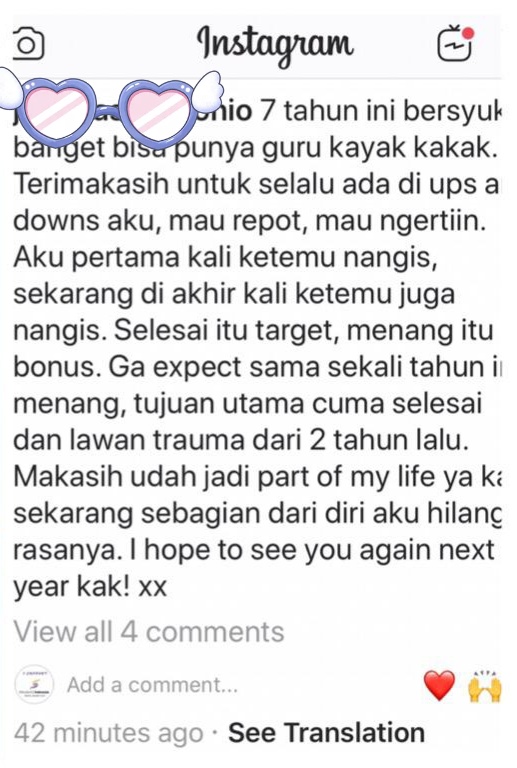
Saya pamit untuk melanjutkan perjalanan.